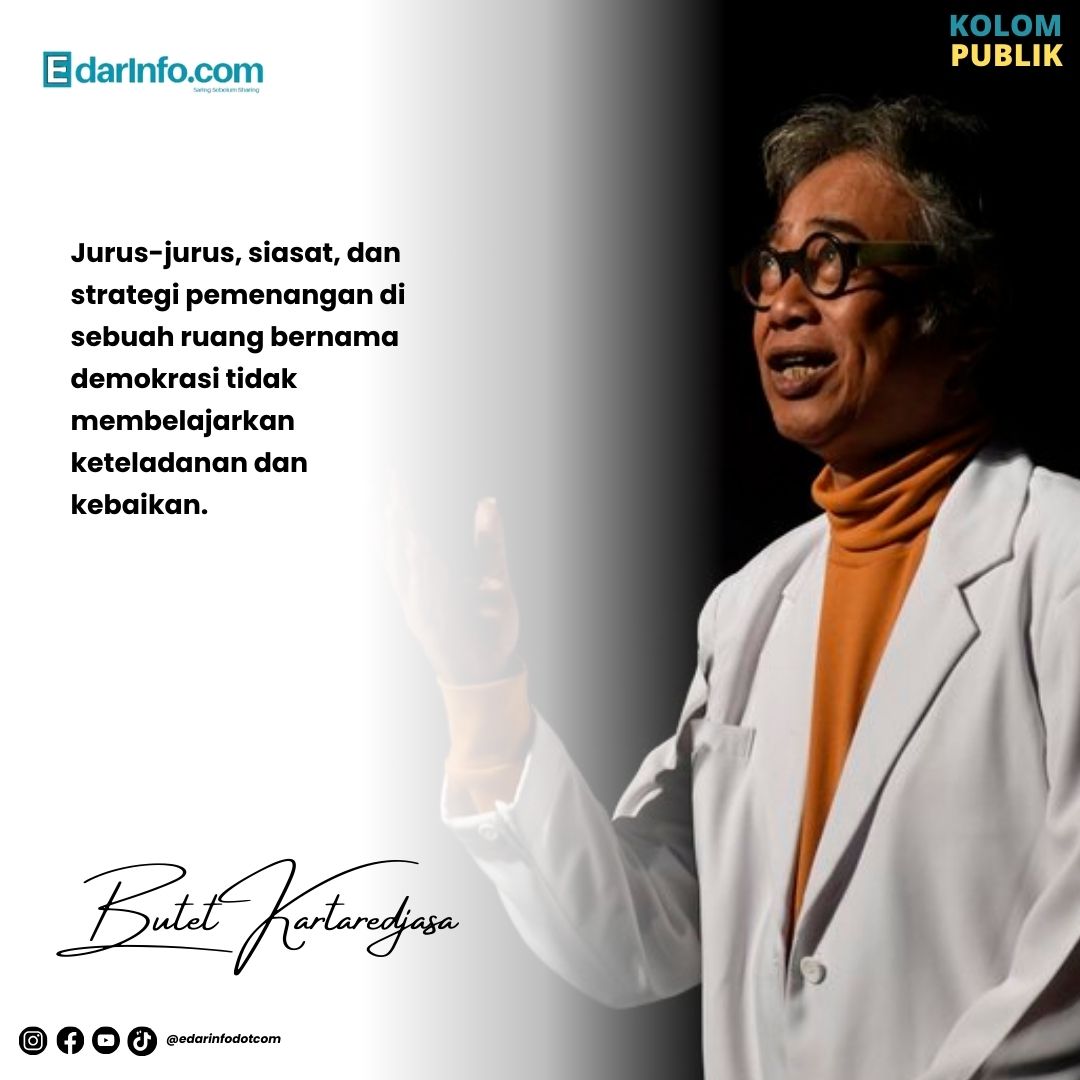Opini, Edarinfo.com– Setiap mengakhiri pertunjukan program ”Indonesia Kita” sejak 2011, saya selalu mengakhiri dengan slogan berupa hasutan seperti judul di atas: ”Jangan kapok menjadi Indonesia!!!”
Sebuah ajakan supaya orang tetap percaya bahwa kita sedang (dan terus) berproses untuk menjadi manusia Indonesia. Percaya keberagaman sebagai keniscayaan dan kekayaan, tentang toleransi, antidiskriminasi, saling menghormati, membangun kesetaraan, indahnya kemajemukan, keinginan mewujudkan keberadilan, menghalau kemunafikan dan pengkhianatan.
Konsep seri pertunjukan ini memang ikhtiar menghayati keindonesiaan melalui jalan kebudayaan. Di ”rumah bersama” itu kita melakukan ibadah kebudayaan. Belajar menjadi Indonesia bukan melalui doktrin dan statement politik.
Di tahun politik yang belakangan terasa mendidih ini—yang menyebabkan kita terkaget-kaget dengan aneka manuver politik para elite dan penguasa— orang harus tetap punya harapan. Jangan putus asa. Tetap berikrar untuk tak akan pernah kapok menjadi Indonesia.
Kita tahu, jurus-jurus permainan dalam kompetisi pemilu kali ini seperti permainan di tepi jurang. Jika tergelincir, yang terpeleset akan ambyar berkeping-keping. Jurus-jurus, siasat, dan strategi pemenangan di sebuah ruang bernama demokrasi tidak membelajarkan keteladanan dan kebaikan.
Catatan ini tak mempersoalkan ”keajaiban” di Mahkamah Konstitusi, karena di media sosial telah bertaburan berbagai analisis yang cerdas, sinis, akademis, spiritualis, lucu, dan sarkastis. Juga tak ikut menggunjingkan lahirnya mentalitas instan-pragmatis yang menyebabkan anak-anak muda sangat bangga jadi benalu. Jadi manusia cangkokan.
Kejatuhan rezeki
Catatan ini hanya ingin mengajak senda gurau. Mengobrolkan hal remeh-temeh sebagai penghibur hati. Sebagai pelarian sekaligus ventilasi kesumpekan hati lantaran menyaksikan akrobat badut-badut politik yang berjumpalitan. Di tengah silang sengkarut ketegangan politik, selalu tercecer kejenakaan. Guyon dan anekdot, termasuk yang mengolok-olok dan meng-karikatur-kan diri sendiri, menjadi benteng terakhir untuk merawat dan menjaga kewarasan kita.
Marilah kita ingat lagi bahasa-bahasa sandi di setiap komunitas. Sandi sesuai daerah asal bernama bahasa gaul, walikan, prokem, plesetan, dan setiap komunitas di lingkup kecil memiliki kode-kode berbahasa sendiri yang khas dan unik. Semula cuma sandi, lama-lama menjadi sehari-hari. Misal, istilah pe-ye yang artinya laku alias payu (Jawa).
Tahun 1960-an ketika seniman masih merasa bertengger di menara gading dan menganggap tabu jika berurusan dengan jasa kreatif, mereka menyembunyikan hal-hal bersifat transaksional dengan sebutan peye. Zaman berganti sehingga peye sudah menjadi kata yang mandiri, bahkan berkembang dalam idiom-idiom baru yang kontemporer.
Misalnya, hari ini ada istilah kepayon party di kalangan seniman perupa Yogya. Artinya perupa kejatuhan rezeki lantaran karyanya terjual, dia akan mengundang kawan-kawan seniman lainnya turut merayakan lewat pesta kecil.
Kepayon party menjadi perekat sosial. Tali jiwa persahabatan, bertemunya kembali canda-tawa, momentum di mana mereka bisa saling membenturkan ide, pemikiran, dan gagasan seni.
Dan seumpama seniman teater ramai-ramai mengunjungi rumah makan, tiba-tiba ada yang mengingatkan, ”Ini Putu Wijaya atau Arifin C Noer?” Lho, apa hubungannya. Bukannya di situ tidak ada dua tokoh teater nasional itu?
Rupanya ini pertanyaan, acara makan ini harus membayar sendiri atau ada yang mentraktir. Sebab, nama grup teater Putu Wijaya namanya Teater Mandiri sehingga masing-masing harus membayar secara mandiri. Dan jika dibayar oleh grup atau ada yang membandari, ini sesuai lakon monolog karya Arifin C Noer, ”Kasir Kita”.
Begitu pun dengan hal-hal sensitif yang berkaitan dengan jasa ekonomi alias upah alias honorarium. Menyebut angka gamblang malu-malu, mereka menyembunyikan dalam sandi, ”Honorku Rahwana mimik anggur.”
Rahwana (Dasamuka, 10 wajah) mimik anggur, artinya Rp 10 (juta) ditambah anggur cap 5.000, alias Rp 15 juta. Yang lain menyambar, ”Wualaaah, aku cuma dapet Dasamuka berwajah Pak Harto.” Artinya lembar duit bergambar Pak Harto, Rp 50.000, dikalikan Dasamuka alias 10; lima ratus ribu saja.
Soal menciptakan sandi harga, hari ini generasi milenial yang sangat bersahabat dengan budaya digital pun punya sandinya sendiri. Kerap membikin generasi analog tergagap-gagap memahami.
Open BO yang bersinggungan praktik prostitusi terselubung yang artinya ’booking’ punya menu dengan password LT (long time) dan ST (short time) dan simbol harganya bukan Rp atau $, melainkan 4A (Rp 400.000), 2B (Rp 100.000), dan selanjutnya bertanyalah kepada anak-adik-cucu kita yang jagoan menerjemahkan isyarat-isyarat itu.
Generasi sepuh paling pol hanya punya istilah sederhana, ”Kopiahan atau Gondrong?”—maksudnya dibayar dengan uang bergambar proklamator yang pakai kopiah atau dollar Amerika yang bergambar tokoh berambut panjang.
AURI banget
Saya yakin masyarakat pasti punya sandi lucu untuk berbagai perkara, termasuk seumpama menilai lawan jenisnya. Begitu pun seumpama dalam percakapan dengan seseorang di ruang publik, kita belum mengenal karakter orang bersangkutan, biasanya dengan cepat bisa merumuskan karakternya dari bahan-bahan percakapan awalnya, orang ini sejenis ”Ateng” atau ”AURI”.
Ateng sebagai penanda ”sok tahu” karena di masa lalu ada film Ateng Sok Tahu yang sangat populer. Dan AURI berarti orang itu bicaranya membubung sangat tinggi, berlebihan congkaknya setinggi Angkatan Udara RI (AURI) menerbangkan pesawatnya.
Waspadalah jika Anda di Yogyakarta terlalu percaya diri dan membual seakan-akan diri Anda paling jagoan, paling hebat, paling bisa menentukan nasib bangsa ini, samar-samar Anda akan mendengar kasak-kusuk, ”Wuaaahhh, ini AURI banget.”
Jika ternyata bualan Anda itu sebuah informasi elementer yang siapa pun sudah tahu, Anda pasti akan disalami, ”Ternyata nama Anda Columbus, ya?”
Maksudnya, orang ini laksana Columbus yang memberi tahu suku Indian kalau dia menemukan dan menceritakan kehebatan Benua Amerika. Bukankah kaum Indian tuan rumah dan suku asli Benua Amerika?
Dari panggung politik hari ini, marilah kita cermati, siapa yang Ateng, AURI, dan Columbus. Atau seumpama butuh simbol lain, siapakah Prabu Belgeduwelbeh alias Petruk dalam lakon ”Petruk dadi Ratu”. Punakawan yang setelah jumeneng menjadi raja—karena kecanduan nikmatnya kekuasaan—lalu malas turun takhta.
Semua yang tergelar ini, bagi seniman, mudah dikapitalisasi sebagai ide-ide kreatif yang inspiratif. Meskipun semua itu harus dijalani dengan kesedihan, dengan air mata kekecewaan.
Menjadi penanda
Sebab, yang dirindukan adalah inspirasi yang membanggakan. Warisan nilai- nilai kebaikan. Nama diri yang populer dan praktik perilaku penuh kebaikan memang bisa menyebabkan nama seseorang menjadi monumen. Namun, ketika ia berada dalam pusaran kontroversi bisa menjadi kata sifat. Menjadi penanda. Simbol. Ia bisa menjadi simbol konotatif sekaligus denotatif.
Bersyukurlah jika orang berhasil mewariskan nama dalam konotasi yang positif, inspiratif, dan terpahat indah dalam bentang sejarah bangsa.
Seperti Bung Karno sebagai bapak bangsa, penggali Pancasila dan proklamator; Bung Hatta sebagai bagian Dwi Tunggal Proklamator dan Bapak Koperasi; BJ Habibie sebagai genius dan bapak inovasi teknologi; dan Abdurrahman Wahid sebagai guru bangsa dan bapak toleransi.
Jika penyair Jokpin, Joko Pinurbo, menuliskan karya legendarisnya: ”Yogya terbuat dari rindu, pulang dan angkringan”, atas seizin penyairnya, saya ingin memelesetkan puisi ini menjadi dua.
”Indonesia terbuat dari apa?
Indonesia terbuat dari benalu, pengkhianatan dan jogetin aja”.
Atau plesetan yang ini:
”Indonesia terbuat dari apa?
Indonesia terbuat dari luka, perjuangan dan air mata”
Kita bebas memilih mana yang kita suka, karena bagi siapa pun hasutan saya konsisten sama; Jangan kapok menjadi Indonesia!!!
Penulis, Butet Kartaredjasa